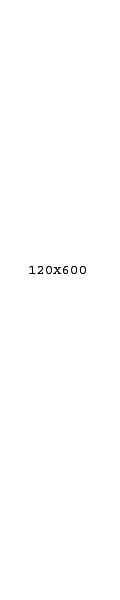Kedua, kebijakan dibuat untuk bisa dipertukarkan dengan suara (transaksional).
Ketiga, kebijakan yang dihasilkan cenderung membebani keuangan negara dan atau menyulitkan kepala pemerintahan terpilih.
Keempat, kebijakan dibuat dengan atensi khusus dan pengawalan langsung oleh policy maker-in-chief. Birokrasi di K/L tak didengarkan lagi suaranya.
Segudang contoh bisa diberikan. Untuk kasus yang paling anyar di negeri ini adalah pembuatan UU ASN, perubahan UU IKN Nusantara, perubahan UU Desa, pembuatan Perpres No 53 Tahun 2023 yang memberlakukan lagi biaya perjalanan lungsum dan mencabut sistem “at cost”, pembuatan kebijakan operasional PSN lewat putusan BP Batam tentang Rempang sebagai Eco-City, rencana perpanjangan periodesasi jabatan presiden dan penundaan pemilu yang telah gagal, dan lain-lain.
Hal yang sama, idem ditto, terjadi pula di tingkat pemda kita. Jelang habis jabatan kepala daerah dan diputarnya pilkada. Bisa ditelisik perda dan perkada yang mereka buat.
Mengingat praktik perilaku tak etis ini semakin merajalela di dalam pembuatan kebijakan publik kita, dan tentu tak mungkin melarang mereka membuat kebijakan sementara mereka masih “in power”, maka sebaiknya ke depan para kepala pemerintahan terpilih baik di tingkat negara dan daerah dibolehkan mengevaluasi langsung kebijakan publik yang dibuat jelang pemilu dan pilkada, dan dapat mencabutnya.