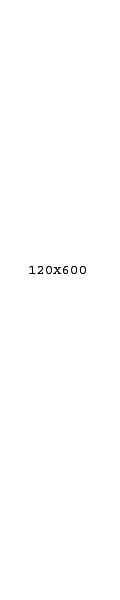Setelah serangan dahsyat ala adegan film perang Vietnam, dilanjutkan dengan “penyanderaan”, hal yang terjadi kemudian sungguh sulit dipercaya. Dalam video viral yang muncul, kita bisa melihat bahwa preman-preman ini, alih-alih buru-buru kabur, justru berpelukan dan cium tangan dengan para aparat yang bertugas.
Barangkali, mereka anggap ini momen emosional, sejenis “Brotherhood of the Street,” di mana mereka berbagi kasih sayang yang lebih mendalam dari sahabat lama yang bertemu kembali setelah puluhan tahun berpisah.
Yang paling menarik dari peristiwa ini adalah peran aparat yang luar biasa. Bukan sebagai pengaman acara diskusi yang digagas para tokoh nasional, tapi sebagai mediator antara perusuh dan pengelola acara.
Aparat dengan sabar menyampaikan pesan-pesan preman kepada peserta. Bisa dibilang, mereka menjalankan tugas bak “account executive” dalam sebuah proyek besar. Setiap keinginan preman disampaikan dengan teliti, seolah preman-preman ini klien VIP yang perlu dilayani dengan penuh perhatian.
Pertanyaannya sekarang: preman ini sebenarnya siapa? Kenapa mereka bisa memerintah aparat? Kenapa aparat keamanan tunduk para mereka?
Apakah ini wujud nyata dari adagium “uang bisa bicara”? Atau jangan-jangan preman ini representasi dari kekuatan lebih besar yang bersembunyi di balik layar?
Dalam situasi ini, kita hanya bisa bertanya-tanya. Yang jelas, peristiwa ini bukan sekadar soal diskusi yang dibubarkan, tapi soal bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia —dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Preman-preman ini, dengan taktik “penyanderaan” ala mafia, telah mengubah dinamika politik Indonesia menjadi lebih absurd dari biasanya. Dalam era ketika orang-orang bicara soal demokrasi dan kebebasan, justru preman-preman-lah yang mengontrol ruang diskusi.
Entah ini parodi dari demokrasi kita, atau sinyal bahwa situasi sedang sangat kacau. Yang jelas, kita sudah semakin jauh dari logika, dan semakin dekat dengan kegilaan.
Pada akhirnya, jika tidak diungkap terang-benderang siapa aktor di baliknya, kasus ini mungkin akan berakhir begitu saja tanpa ada konsekuensi besar. Preman-preman akan kembali ke jalanan, mungkin dengan cerita baru tentang bagaimana mereka berhasil menyandera tokoh nasional.
Aparat pun akan kembali melanjutkan tugas mereka, mungkin dengan pelajaran baru tentang cara menengahi konflik antara diskusi intelektual dan premanisme. Sementara kita, rakyat biasa, hanya bisa tertawa getir, menonton sandiwara ini berlanjut tanpa henti.[***]